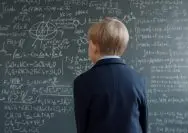JATENGKU.COM, SURABAYA — Tahun 2025, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek), mulai menerapkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai bagian dari seleksi perguruan tinggi. Asesmen ini dijalankan karena beberapa tahun terakhir muncul permasalahan yang disebabkan adanya pandangan subjektif terhadap nilai rapor, penilaian yang berbeda sesuai dengan kebijakan sekolah, dan kebutuhan seleksi yang di anggap lebih adil.
TKA bersifat tidak wajib, tetapi hasilnya dapat menjadi tolak ukur untuk seleksi di jenjang pendidikan selanjutnya, hasil TKA juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lainnya. Soal-soal yang di ujikan menekankan pada pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis diharapakan mampu memetakan kemampuan akademik siswa. Namun dibalik tujuannya, implementasi TKA menimbulkan konflik yang dipertanyakan oleh publik, apakah TKA benar-benar menciptakan keadilan atau ketidaksetaraan baru di dunia pendidikan?
Pemerintah mempromosikan TKA sebagai instrumen menilai kemampuan siswa yang terstandar tanpa bergantung hafalan materi pelajaran. Hal ini sejalan dengan kurikulum saat ini yang menekankan kemampuan bernalar kritis, literasi, dan pemecahan masalah. TKA diharapkan dapat menjadi solusi keseragaman nilai siswa, sehingga hasil seleksi perguruan tinggi tidak hanya mengandalkan penilaian internal sekolah. Di mana ketidakadilan muncul karena setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan nilai siswa, ada yang cenderung memberi nilai tinggi, ada pula yang memberi nilai secara konservatif.
Namun, saat pengimplementasiannya timbul beberapa tantangan, masalah yang paling utama adalah infrastruktur yang tidak merata. Karena TKA diadakan berbasis komputer, beberapa sekolah tidak memiliki laboratorium komputer yang memadai atau bahkan tidak memiliki fasilitas komputer. Sekolah dengan fasilitas komputer yang terbatas akan mengalami kesulitan baik dalam sisi teknis maupun perangkat, jaringan yang tidak stabil, atau tidak memiliki teknisi yang kompeten. Hal ini menjadikan siswa pada wilayah 3T atau sekolah yang fasilitasnya tidak memadai berada pada posisi tidak menguntungkan. Dalam konteks ini, TKA ini menjadi pengingat bahwa adanya ketimpangan yang belum terselesaikan.
Selain keterbatasan insfrastuktur, adanya fenomena yang sudah lama menjadi bagian dari sistem seleksi perguruan tinggi, yaitu bimbingan belajar (bimbel) juga menjadi tantangan. Walaupun pemerintah menekankan bahwa TKA tidak memerlukan kesiapan khusus dan soal-soalnya berbasis pada kemampuan bernalar serta tidak mengandalkan hafalan, banyak siswa merasa perlu mengikuti bimbingan belajar untuk mengahadapi pola soal-soal baru. Bimbel menawarkan kelas intensif TKA, lengkap dengan pembahasan soal dan simulasinya. Hal ini tentu menguntungkan siswa yang berasal dari keluarga mampu, mereka cenderung lebih mudah mendapatkan pendampingan diluar sekolah yang mungkin tidak didapatkan oleh beberapa siswa yang lain.
Masalah lain muncul dari sisi transparansi penilaian dan pemanfaatan TKA. Pemerintah menyatakan bahwa TKA digunakan untuk mengonfirmasi nilai rapor, tetapi bagaimana penafsiran perbedaan nilai belum jelas mekanismenya. Apakah jika nilai TKA lebih kecil dari nilai rapor maka sekolah di anggap tidak objektif? Apakah siswa akan mendapatkan konsekuensi tertentu? Bagaimana indikator ketidaksesuaian ditentukan? Kurangnya kejelasan ini menimbulkan kekhawatiran baik pada siswa maupun sekolah, justru kebijakan ini menimbulkan ruang spekulasi.
Terlepas dari berbagai kritik dan tantangan yang muncul, TKA tetap memiliki sisi positif. Jika dilaksanakan dengan adil dan adanya pemerataan fasilitas, TKA dapat meningkatkan kualiatas pendidikan. Hasil TKA dapat menjadi evaluasi bagi sekolah dan pemerintah bagaimana kekuatan dan kelemahan proses belajar di berbagai daerah. Agar hal ini dapat berjalan tentunya didukung dengan pemerataan akses TKA, di mulai dari dukungan penuh dalam pemberian fasilitas yang memadai, pelatihan guru, serta penyediaan simulasi gratis. Tanpa adanya dukungan tersebut, TKA justru hanya pintu yang dapat dilalui oleh sebagian siswa.
Maka dari itu, pengembangan TKA harus dibarengi dengan kesiapan sekolah. Pemerintah dapat membantu dengan memastikan setiap sekolah memiliki fasilitas komputer, akses internet yang stabil, serta pelatihan terhadap guru dan teknisi. Selain itu, penting untuk memastikan materi TKA seperti latihan soal atau simulasi resmi dapat diakses secara gratis seluruh siswa. Hal ini akan mengurangi ketimpangan sosial dan meminimalkan ketergantungan terhadap bimbingan belajar.
Pada akhirnya, TKA seharusnya dapat menjadi alat pemerataan pendidikan, bukan menciptakan kesenjangan baru di balik kata “standarisasi”. Keadilan tidak berdasarkan pada suatu kebijakan tapi bagaimana kesiapan sistem pendidikan memastikan seluruh siswa memiliki kesempatan untuk berhasil tanpa memandang latar belakang. Jika pemerintah mampu mengelola TKA dengan baik, akan tercipta kualitas pendidikan yang lebih baik.
Penulis: Cherrie Putri Nuralifia Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga