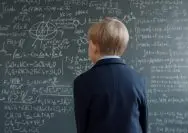JATENGKU.COM, Surabaya — HIV/AIDS telah lama menjadi isu kesehatan global yang penuh stigma, kesalahpahaman, dan rasa takut. Di kalangan mahasiswa, topik ini tidak jarang dikaitkan dengan meningkatnya pergaulan bebas—sehingga mudah disimpulkan bahwa bertambahnya angka kasus berarti perilaku seksual yang semakin tidak terkendali. Namun, apakah benar demikian? Atau justru kita melihat gejala positif berupa meningkatnya kesadaran untuk memeriksakan diri?
Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS pada kelompok usia produktif, termasuk mahasiswa. Akan tetapi, tenaga kesehatan melihat hal ini dari sudut pandang lain. Angka yang tinggi tidak selalu berarti penyebaran virus semakin meluas—melainkan bisa menjadi sebuah indikator bahwa semakin banyak orang yang berani memeriksakan diri dan meninggalkan stigma yang selama ini menutup realita sesungguhnya. Kesadaran itulah yang sebenarnya menjadi titik terang dalam upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS.
Meluruskan Persepsi: Kasus Meningkat, Perilaku Belum Tentu Bertambah
Jika dibandingkan dengan beberapa dekade lalu, cara masyarakat memandang HIV/AIDS mulai mengalami pergeseran. Dulu, pemeriksaan HIV merupakan sesuatu yang dianggap tabu, menakutkan, atau bahkan memalukan. Orang memilih untuk diam dan bersembunyi, bahkan ketika sudah merasakan gejala yang mengganggu kesehatan. Padahal, semakin lama seseorang menunda diagnosis, semakin besar risiko penularan dan semakin sulit proses terapi.
Kini kesadaran itu mulai tumbuh, terutama di kalangan generasi muda. Banyak mahasiswa yang secara sukarela mendatangi fasilitas kesehatan untuk melakukan skrining HIV tanpa harus menunggu gejala muncul. Mereka ingin tahu kondisi tubuhnya lebih cepat—agar bisa menjaga diri sendiri dan orang sekitar. Inilah yang membuat data terlihat meningkat. Dengan kata lain, kenaikan data justru menandakan bahwa deteksi dini semakin berjalan baik.
Kesalahan umum dalam membaca data adalah menyamaratakan bahwa peningkatan angka selalu berarti peningkatan perilaku berisiko. Padahal data statistik kesehatan tidak dapat dibaca secara kaku. Proses edukasi, penyediaan layanan kesehatan, dan penyebaran informasi kesehatan reproduksi justru menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap status kesehatannya. Ini adalah kemajuan sosial yang patut diapresiasi.
Peran Lapangan: Belajar Langsung dari Realita Sosial
Dunia medis tidak hanya bergelut dengan jurnal, teori, atau peralatan laboratorium. Kesehatan masyarakat tidak bisa dipahami secara utuh tanpa turun ke lapangan dan mengamati kondisi sosial masyarakat secara langsung. Setiap daerah memiliki budaya, kebiasaan, tingkat pendidikan, hingga gaya komunikasi yang berbeda—dan semua itu memengaruhi pendekatan medis.
Sebagai contoh, ada daerah dengan tingkat penyakit infeksi yang tinggi, tetapi tingkat kesadaran kesehatan sangat rendah. Sebaliknya, ada pula daerah yang tampak baik-baik saja secara statistik, tetapi memiliki masalah kesehatan reproduksi yang tidak terlihat karena tidak banyak orang yang bersedia melapor. Inilah sebabnya penanganan kesehatan tidak boleh hanya mengandalkan teori, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial setempat.
Sering kali penanganan medis keliru karena berangkat dari asumsi yang terlalu teoretis. Data statistik memang penting, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggambarkan konteks budaya, rasa takut, atau tabu yang hidup di tengah masyarakat. Maka, observasi lapangan adalah kunci untuk memahami akar masalah dan menentukan strategi pencegahan yang tepat sasaran.
Tantangan Pendidikan Kedokteran: Antara Adaptasi dan Ketahanan Mental
Di balik pemahaman tentang HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi, terdapat realitas lain yang tidak kalah penting: membentuk tenaga kesehatan yang siap secara mental, emosional, dan sosial. Pendidikan kedokteran sering dianggap berat dan penuh tekanan, tetapi kesulitan tersebut sebenarnya bisa diatasi jika mahasiswa mampu menemukan pola belajarnya sendiri.
Mahasiswa baru sering merasa takut mendengar stigma “FK itu berat”, padahal kesulitan belajar adalah hal yang wajar dalam semua jenjang pendidikan. Kunci utama adalah adaptasi: memahami lingkungan baru, membentuk relasi yang sehat, mengetahui karakter dosen, serta mengenali gaya soal ujian. Ketika pola belajar sudah dipahami, rasa takut akan berkurang dan proses belajar menjadi lebih efektif.
Selain itu, keterlibatan dalam organisasi tidak boleh dianggap sebagai hambatan. Justru dari kegiatan sosial inilah mahasiswa belajar komunikasi, tanggung jawab, manajemen waktu, dan empati—hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam profesi medis. Selama ada kemauan untuk menghadiri kegiatan, menyelesaikan tugas, dan terus berproses, akademik dan organisasi dapat berjalan berdampingan.
Ketika memasuki tahap koas, tantangan menjadi lebih nyata. Tenaga dan mental harus dipersiapkan. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar, dan rasa minder tidak boleh menghalangi perkembangan diri. Yang dibutuhkan adalah ketahanan mental dan semangat untuk memperbaiki diri. Dalam dunia medis, kegigihan jauh lebih penting daripada kesempurnaan.
Seksualitas dan Kualitas Hidup: Aspek yang Sering Diabaikan
Topik mengenai seksualitas, infertilitas, dan kesehatan reproduksi sering dianggap tabu untuk dibahas secara terbuka. Padahal penelitian menunjukkan bahwa aspek tersebut sangat menentukan kualitas hidup seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Seksualitas yang sehat bukan hanya soal aktivitas biologis, tetapi juga menyangkut hubungan interpersonal, rasa percaya diri, kesehatan mental, dan kesejahteraan secara keseluruhan.
Sayangnya, banyak orang justru menghindari diskusi tentang pendidikan seksual karena takut dianggap mendukung pergaulan bebas. Padahal edukasi seksual adalah perlindungan, bukan pengesahan. Semakin dini edukasi diberikan, semakin besar peluang untuk mencegah penularan penyakit dan menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan.
Mahasiswa kedokteran pun belajar bahwa tugas tenaga kesehatan adalah memberikan pengetahuan, bukan menghakimi. Edukasi yang baik tidak menakut-nakuti, tetapi membantu masyarakat memahami tubuhnya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Dengan pemahaman yang benar, keputusan yang lebih bijak akan dibuat—dan inilah fondasi utama dari kesehatan reproduksi masyarakat.
Stigma: Hambatan Terbesar dalam Penanganan HIV/AIDS
Meski akses informasi semakin luas, stigma terhadap HIV/AIDS masih sangat kuat. Banyak orang takut memeriksakan diri karena khawatir akan dihakimi. Padahal HIV bukan hukuman moral, melainkan kondisi medis yang dapat dikelola. Sudah banyak bukti bahwa seseorang dengan HIV dapat menjalani hidup normal selama mendapat terapi yang tepat.
Stigma adalah musuh utama dari deteksi dini. Jika masyarakat takut diperiksa, maka virus akan lebih mudah menyebar tanpa terdeteksi. Karena itu, perubahan pola pikir masyarakat sangat penting. Edukasi harus berjalan beriringan dengan empati. Tenaga kesehatan perlu memahami bahwa penyembuhan tidak hanya terjadi melalui obat, tetapi juga dari rasa diterima dan dipahami.
Penutup: Edukasi Adalah Bentuk Perlindungan
Pada akhirnya, HIV/AIDS bukan sekadar isu kesehatan, tetapi gambaran hubungan manusia dengan pengetahuan, empati, dan tanggung jawab sosial. Daftar angka kasus memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memahami cerita di balik angka tersebut.
Edukasi seksual yang ilmiah dan terbuka bukan ancaman moral, melainkan pelindung generasi muda dari risiko kesehatan yang serius. Yang tabu tidak perlu dihindari, tetapi harus dibahas dengan bijaksana dan berdasarkan ilmu. Jika empati menjadi dasar dari semua proses penyembuhan, maka tenaga kesehatan bukan hanya menjadi penyembuh fisik—melainkan penggerak perubahan sosial.
Sebagai generasi calon tenaga kesehatan, pemahaman dan kesadaran adalah obat pertama yang harus diberikan pada masyarakat. Melalui usaha seperti ini, kita dapat menciptakan lingkungan kampus dan sosial yang sehat, informatif, dan bebas stigma—tempat di mana kesehatan bukan hanya ketiadaan penyakit, tetapi hadir sebagai kualitas hidup yang utuh.
Daftar Pustaka
- WHO. (2023). Global HIV/AIDS Progress Report. World Health Organization.
- UNAIDS. (2022). Key Populations and HIV Prevention Strategies. UNAIDS
- Santrock, J. W. (2021). Adolescence: Development and Challenges. McGraw-Hill.
- UNESCO. (2022). Sexuality Education for the 21st Century. Paris: UNESCO Publishing.
- Rahmawati, N. (2020). Stigma Sosial HIV/AIDS di Kalangan Remaja. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 12(1), 44–52.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Laporan Situasi HIV/AIDS di Indonesia. Kemenkes RI.
- Mustika, A. (2021). Dampak Psikologis HIV pada Mahasiswa. Journal of Youth Health, 4(2), 77–85.

Penulis: Shaina Angelica Putri Riandi, Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga