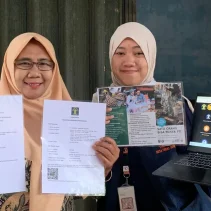JATENGKU.COM, Surabaya — Pernyataan salah satu Wakil DPR RI yang berpendapat bahwa ahli gizi tidak diperlukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan perdebatan luas, terutama di kalangan tenaga kesehatan, akademisi, dan penggiat pelayanan gizi masyarakat.
Pernyataan tersebut bukan hanya memantik respons emosional, tetapi juga menegaskan kembali pentingnya tata kelola kebijakan yang lebih didasarkan pada bukti ilmiah (evidensi) dan bukan hanya pertimbangan praktis, terutama mengingat program ini krusial bagi pengembangan SDM..
Program MBG pemerintah dirancang untuk memperbaiki status gizi anak sekolah, menekan angka kekurangan energi kronis, dan mendukung pencapaian target perbaikan kualitas SDM nasional sambil menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan UMKM daerah.
Mengingat beban permasalahan gizi yang masih signifikan di Indonesia, mulai dari stunting yang masih berada di kisaran 21%, tingginya kasus anemia pada remaja, dan kesenjangan akses pangan antardaerah membuat kehadiran tenaga profesional kesehatan menjadi komponen penting dalam memastikan program berjalan secara aman, efektif, dan tepat sasaran.
Ahli gizi memegang peran penting dan terukur dalam layanan berbasis pangan, sebagaimana dibuktikan oleh praktik lapangan di berbagai wilayah. Peran kritis mereka meliputi analisis mendalam terhadap kebutuhan gizi anak dengan mempertimbangkan usia, aktivitas, dan kondisi kesehatan (misalnya alergi), mengingat kebutuhan energi dan zat gizi sering kali berbeda.
Selanjutnya, ahli gizi bertanggungjawab untuk merencanakan menu seimbang sesuai Angka Kecukupn Gizi (AKG) anak usia sekolah. Fungsi penting lainnya adalah pengawasan ketat terhadap keamanan dan higienitas pangan, memastikan bahan baku memenuhi standar (kesegaran, keamanan), mengontrol proses memasak, serta mengawasi standar porsi dan pengemasan.
Selain itu, ahli gizi wajib melakukan monitoring dan evaluasi rutin status gizi melalui penimbangan dan pengukuran antropometri. Terakhir, mereka berperan sebagai pendidik gizi bagi siswa, guru, dan orang tua, sebuah intervensi yang penting untuk memastikan anak-anak mempertahankan pilihan makanan sehat. Keseluruhan fungsi profesional ini sangat penting dan tidak dapat dialihkan kepada staf non-profesional tanpa membahayakan standar mutu program.
Meskipun peran ahli gizi terbukti sangat penting dan tidak dapat digantikan untuk menjaga mutu dan keamanan program, fakta di lapangan menunjukkan adanya masalah nyata terkait profesi ahli gizi yang belum terdistribusi secara merata. Namun, kondisi ini sama sekali bukan pembenaran untuk meniadakan peran ahli gizi dari program MBG.
Sebaliknya, program MBG seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang strategis untuk mengatasi kekurangan SDM tersebut dengan cara meningkatkan penempatan ahli gizi di institusi pendidikan, memperkuat kolaborasi atau jejaring kerja antara sekolah dan puskesmas, serta menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib melibatkan tenaga profesional.
Menghapus ahli gizi dari program tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan dianggap sebagai langkah mundur dalam tata kelola kesehatan masyarakat.
Kegagalan untuk memanfaatkan momentum ini justru akan memicu serangkaian risiko fatal. Jika layanan gizi tidak diawasi oleh tenaga profesional, maka dapat menimbulkan masalah seperti ketidaktepatan porsi yang gagal memenuhi kebutuhan energi anak usia sekolah dan kualitas menu yang tidak seimbang (cenderung tinggi karbohidrat dan rendah protein akibat fokus pada harga, bukan gizi).
Selain itu, risiko keamanan pangan meningkat karena banyak dapur sekolah yang tidak memenuhi standar sanitasi tanpa pengawasan ahli. Akibatnya, terjadi pemborosan anggaran karena tidak adanya perhitungan gizi dan biaya yang akurat. Yang paling penting, program ini berisiko gagal mencapai target perbaikan gizi nasional, mengingat keberhasilan program makan sehat di negara lain sangat bergantung pada keterlibatan ahli gizi sejak tahap perencanaan.
Potensi kegagalan dan risiko ini diperburuk oleh Dampak Pernyataan Pejabat Publik, di mana pandangan dan komentar dari elite politik memiliki efek yang sangat langsung dan signifikan terhadap birokrasi dan pelaksana program di lapangan. Jika pejabat publik menyampaikan pandangan bahwa tenaga gizi tidak terlalu penting atau dapat dikesampingkan, maka dampaknya dapat berupa penurunan alokasi anggaran daerah untuk kegiatan supervisi gizi.
Selain itu, sekolah cenderung merasa cukup mengandalkan tenaga dapur tanpa perlu melibatkan pengawasan profesional, yang pada akhirnya menyebabkan kualitas program menurun karena tidak adanya standar yang tegas. Dalam konteks tata kelola publik modern, kebijakan harus berlandaskan bukti faktual (evidence-based policymaking), bukan sekadar preferensi praktis atau asumsi. Oleh karena itu, program sebesar MBG memerlukan pendekatan lintas profesi yang komprehensif, dan tidak boleh disederhanakan dengan mengabaikan peran vital ahli gizi.
Oleh karena itu, alih-alih mengesampingkan peran ahli gizi hanya karena kekhawatiran ketersediaan SDM, pemerintah seharusnya fokus pada Alternatif Solusi yang Lebih Realistis dan Berbasis Fakta yang bertujuan memperkuat sistem yang sudah ada.
Opsi kebijakan yang realistis mencakup penempatan tenaga gizi per klaster sekolah atau per kecamatan untuk optimalisasi jangkauan; memberikan pelatihan dasar gizi kepada pengelola dapur sekolah, yang kemudian wajib menerima supervisi berkala dari ahli gizi; dan mempererat kemitraan antara sekolah dan puskesmas untuk pemantauan gizi terpadu.
Selain itu, diperlukan penyusunan standar menu nasional yang fleksibel agar dapat diadaptasi sesuai kondisi daerah, serta penetapan monitoring status gizi siswa sebagai indikator keberhasilan program. Pendekatan berbasis fakta ini dinilai jauh lebih efektif dan rasional daripada mengambil langkah mundur dengan menghapus peran profesional gizi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang menyimpan potensi luar biasa sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan jangka panjang generasi muda Indonesia. Namun, keberhasilan sebuah program publik yang masif tidak dapat dijamin hanya oleh besarnya alokasi anggaran atau sekadar niat baik; keberhasilan sejati ditentukan oleh fondasi keilmuan yang akurat, kepatuhan pada standar profesional, dan kualitas implementasi di lapangan.
Oleh karena itu, langkah mengurangi peran ahli gizi sama artinya dengan menurunkan mutu program secara keseluruhan dan mengabaikan bukti ilmiah serta fakta praktis yang telah teruji. Jika aspirasi kita adalah melahirkan Generasi Emas yang unggul, maka sudah seharusnya kebijakan yang diambil didasarkan pada keahlian profesional dan data yang valid, bukan sekadar pertimbangan praktis atau asumsi belaka.
Penulis: Talenta Enzelyne, Mahasiswi Program Studi Gizi Universitas Airlangga